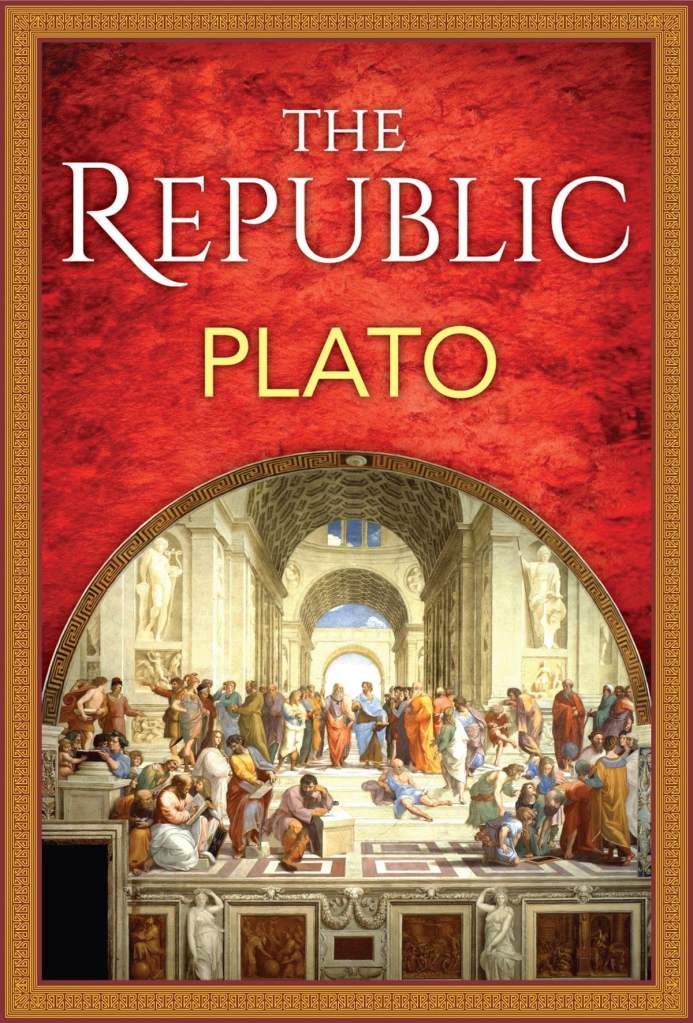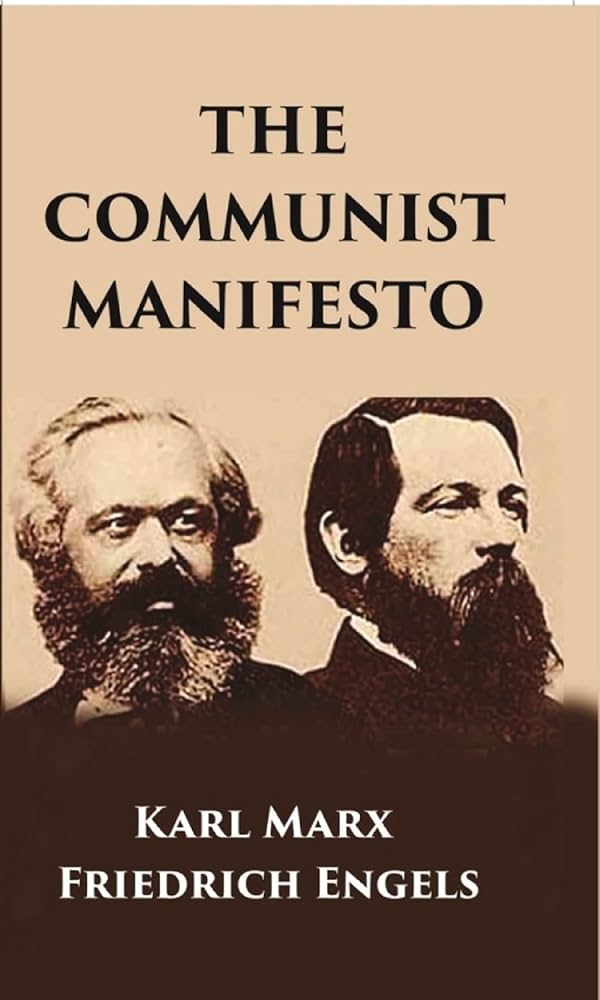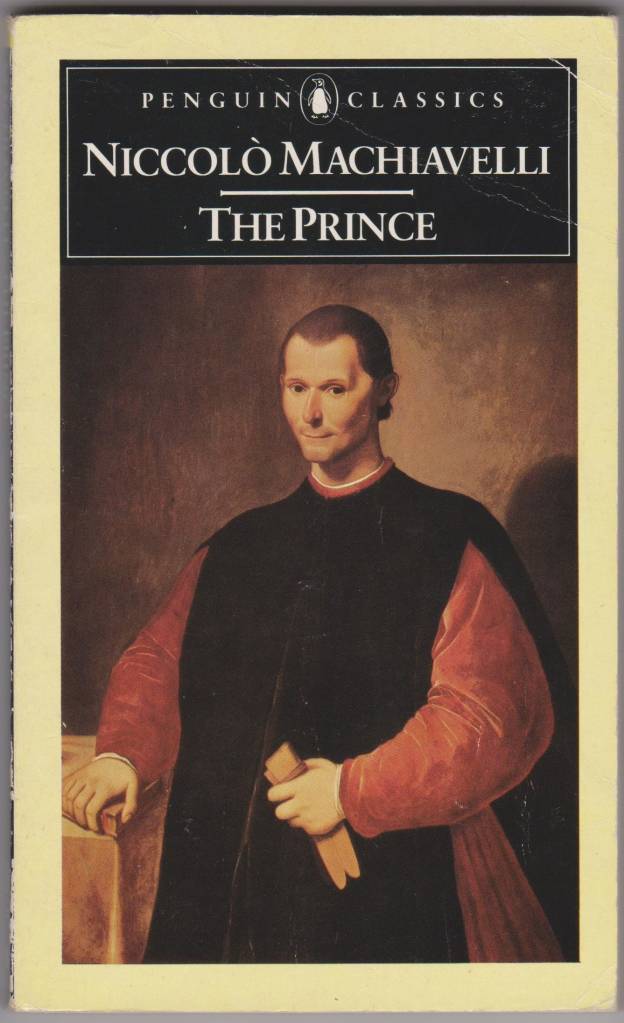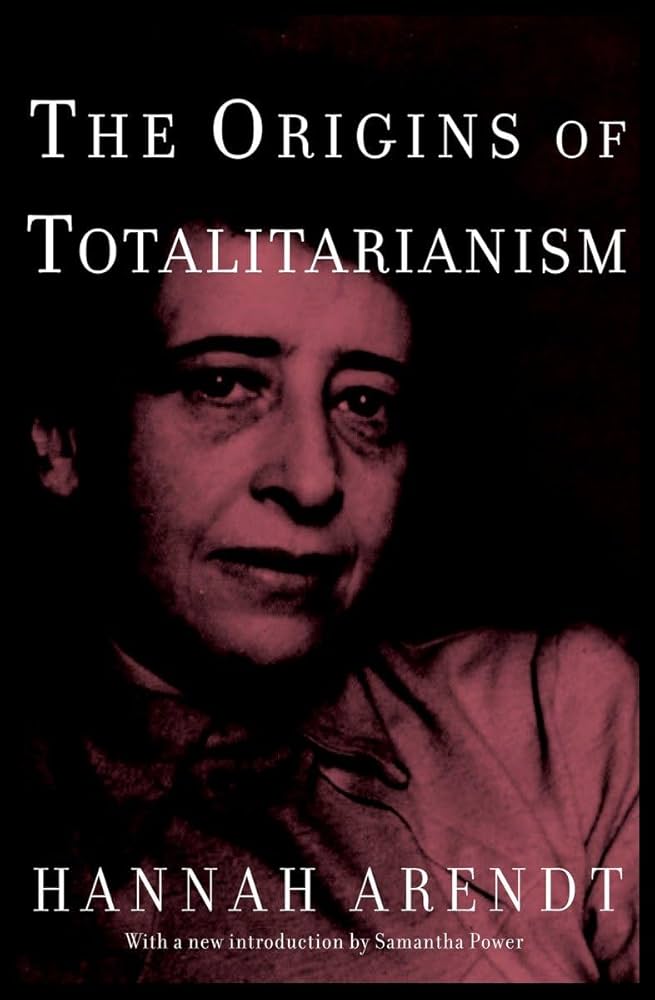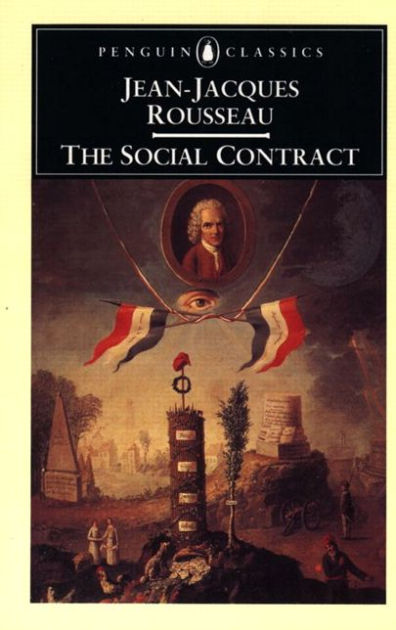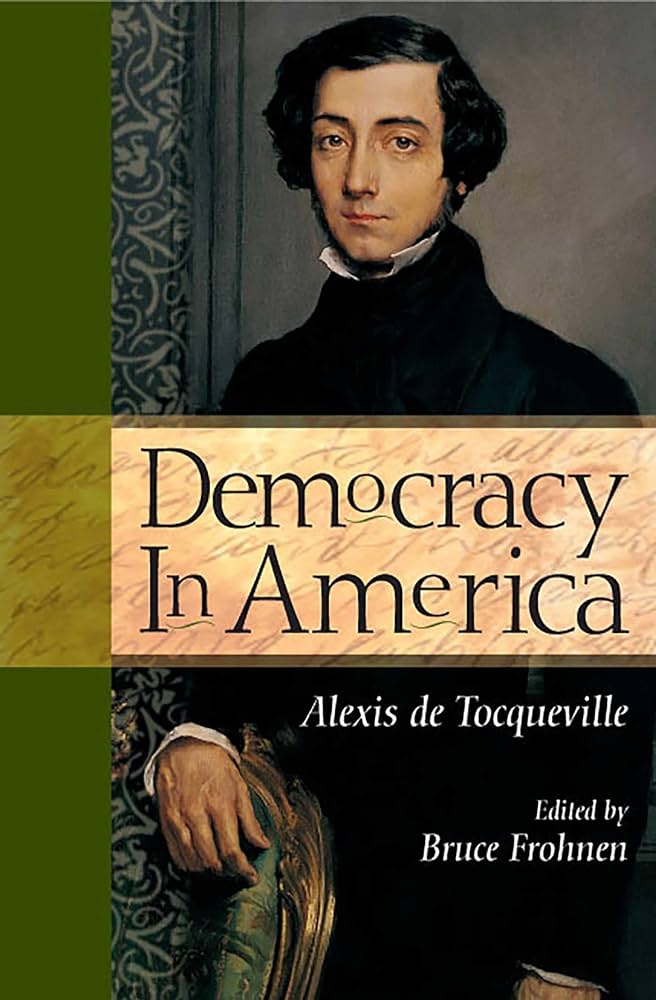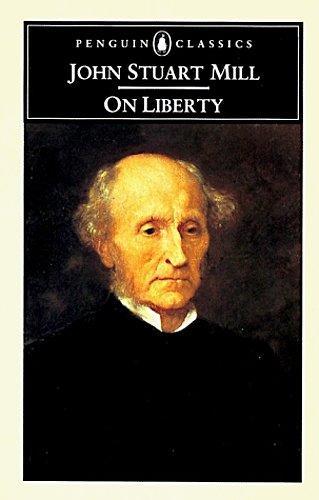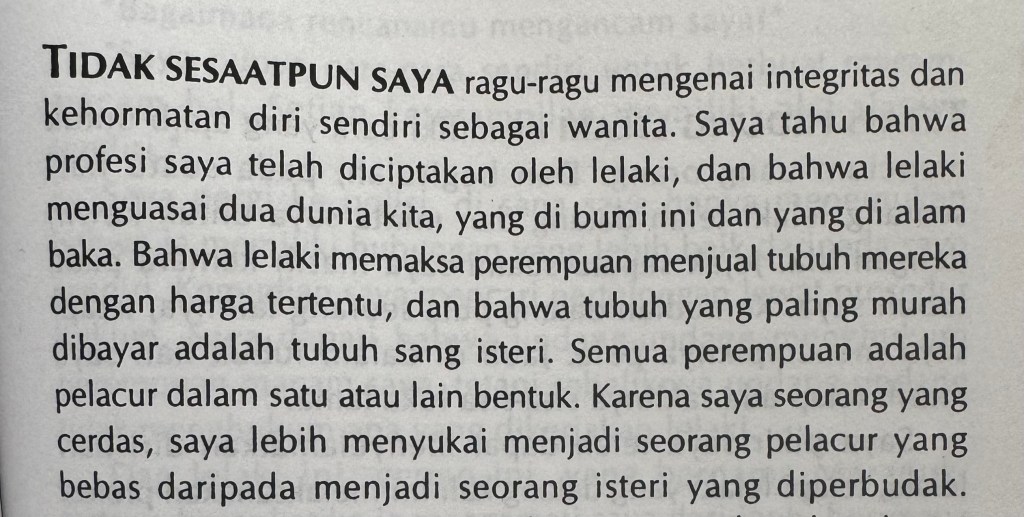Sebenarnya tidak hanya seorang kawan, karena Favour-pun adalah kolega di kantor, anggota tim di OO (nama kantor). Usianya paling muda, tapi karena latar belakangnya dari hukum, sesuai dengan bidang pekerjaan, dan dia memang pintar di bidangnya, membuat karirnya cukup melesat, sampai akhirnya sekarang berada di posisi Senior Country Manager untuk wilayah Afrika. Karena pekan kemarin ada kegiatan lokakarya di Jakarta, dia pun akhirnya datang ke kota ini, yang tidak kusangka ternyata adalah kota Asia pertamanya. Ternyata dia belum pernah ke benua Asia sama sekali sebelumnya. Yah, sama saja denganku yang belum juga kunjung ada kesempatan ke benua Afrika.
Di hari terakhir dia di Indonesia, setelah satu pekan lokakarya dan empat hari terakhir dia habiskan dengan berlibur ke Bali sendirian, akhirnya kami jalan berdua. Janjian di Grand Indonesia (GI), karena dia bersikeras ingin ke satu tempat di mall itu untuk menyantap satu makanan yang menurutnya nikmat sekali. Dia ingin makanan itu lagi sebelum pulang ke negaranya. Penasaran, akupun mengiyakan. Aku sampai penasaran makanan apa yang dia maksud. Terlebih karena dia menyebutkan nama tempatnya adalah Three Uncles, tempat di GI yang belum pernah aku datangi. Saat sudah sampai, aku biarkan dia pesan, dan ternyata, oh la la, ternyata dia pesan nasi goreng!! “Ooohhh nasi goreeeng”, kataku. “Ya ya”, katanya. Dari percakapan kami, sepertinya dia tidak tahu bahwa nasi goreng dan fried rice merujuk pada makanan yang sama. Tapi baiklah, ini jadi memberikanku referensi, bahwa orang asing memang suka dengan nasi goreng. Lain kali, kalau ada kawan asing lainku datang, kuajak saja ke tempat seperti ini.
Kami pun berbincang tentang banyak hal, baik personal maupun profesional. Menariknya, Favour memang tipe orang yang hidupnya sangat didekasikan untuk pekerjaan, seolah-olah pekerjaannya lah yang mendefinisikan dirinya. Hasilnya, saat rapat ataupun bicara santai seperti ini, tata bicaranya tetap formal, dan dia akui itu. Sesama orang lokal (di negara masing-masing) yang bekerja di lembaga internasional, kurang lebih kami memiliki kesamaan, maka kubagikan lah beberapa pandanganku juga tentang ini. Salah satunya adalah tentang dinamika bagaimana kami harus membawa diri saat menghadapi pemerintah setempat. Bahwa walaupun kami representatif dari kantor global yang berusaha menawarkan solusi, kami harus tetap punya kerendahan hati untuk menyampaikan bahwa pemerintah tersebut lah yang lebih mengerti tentang isu terkait negaranya, caranya adalah saat datang mengenalkan diri, kami tidak bilang “we are the experts”, tapi justru memilih diksi ” we are people with expertise”. Ternyata hal sepele seperti itu saja bisa jadi signifikan beda hasilnya.
Setelah berbincang panjang lebar, akhirnya kami pun bersegera pergi, karena Favour sudah harus ke bandara. Tapi sebelum itu, dia ingin beli oleh-oleh kopi Indonesia, dan kuarahkan ke booth kopi Tanamera, karena itu kopi andalan suamiku juga sehari-hari. Karena uang rupiah dia kurang, kuminta saja uang itu, biar jadinya aku yang bayar ke kasir pakai QRIS. Melihat aku bayar, dia ternyata terkesan, karena di Indonesia bisa cukup scan barcode seperti itu. Aku sampaikan bahwa penggunaan QRIS sudah umum di negara ini, bahkan untuk sekadar beli jajanan di jalan. Sedikit banyak aku jadi bangga dengan kemajuan negara ini, walau aku tak sempat tanyakan balik apa di Nigeria sudah mulai mengadopsi teknologi yang sama. Selain kopi, kubelikanlah juga dia eskrim andalanku setiap ke GI, yaitu eskrim buah dari Paletas Way terbaik.
Pertemuan berakhir, kami pun berpelukan tanda perpisahan, berjanji akan bertemu lagi di bagian dunia yang lain. Semoga berikutnya aku yang giliran ke Afrika. Amin.
Jakarta, 30 Agustus, 9 hari setelah jalan-jalan di GI
Haniwww