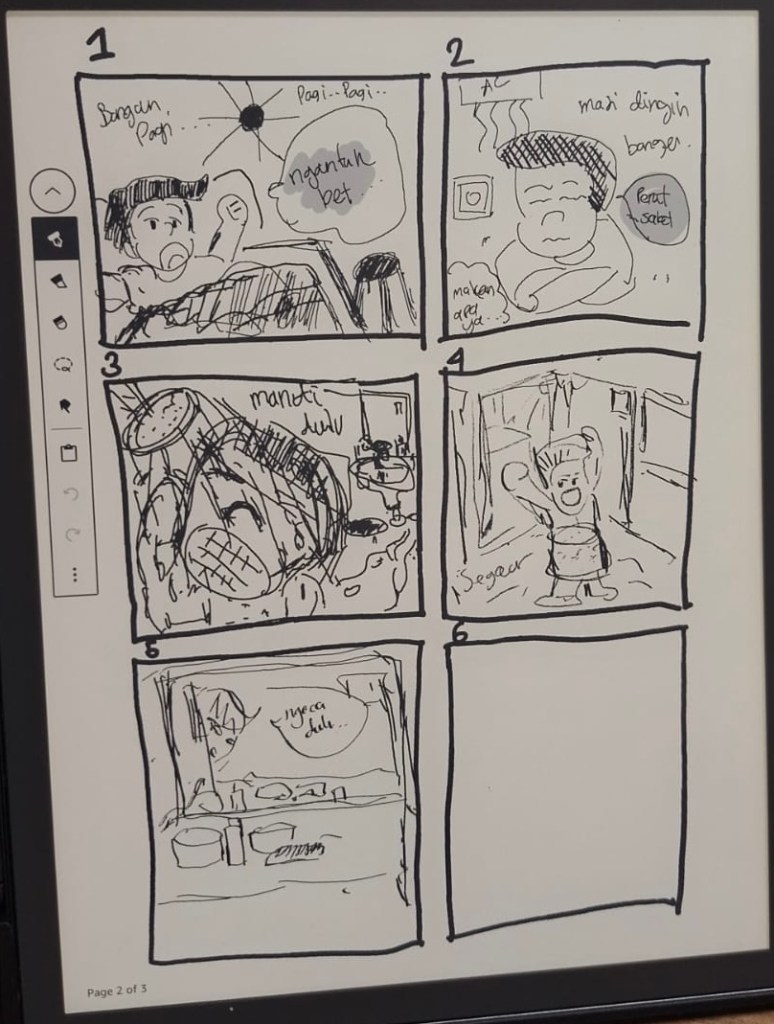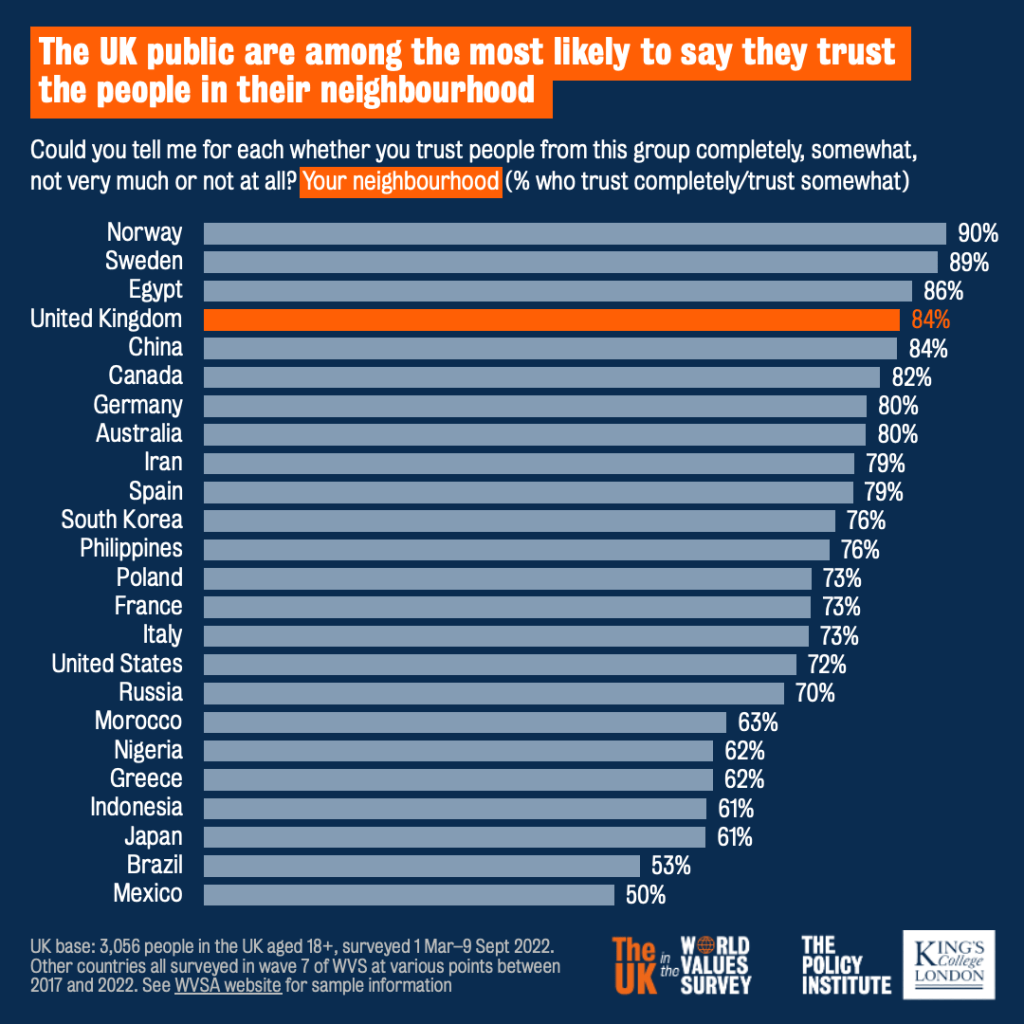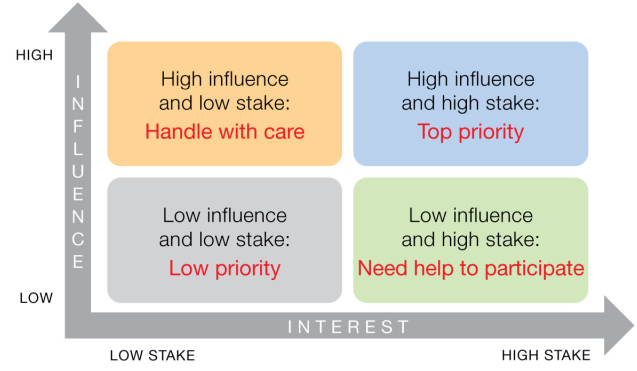Kejadiannya beberapa bulan yang lalu. Di satu malam, saya syok karena mendapat kabar salah satu keponakan saya (putra dari sepupu) meninggal dunia. Usianya masih 4 tahun 10 bulan, persis 2 bulan lagi mencapai ulang tahun ke-5 andai saja dia tidak berpulang. Ya bagaimana tidak syok, baru kurang dari dua hari sebelumnya dia tiba-tiba masuk rumah sakit karena demam tinggi. “DBD, kayaknya”, kata orang-orang. Tapi dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin kami sekeluarga siap menerima kabar duka. Saat itu juga saya yang sedang di Jakarta langsung buru-buru naik travel menuju Bandung, sampai di Bandung hampir jam 1 pagi. Saat saya sampai, jenazah sudah dimandikan, dikafani, dan ditutup oleh kain motif batik warna cokelat. Saya jadi tidak sempat melihat wajahnya untuk terakhir kali, hanya mendengar bagaimana kondisinya dari orang-orang, termasuk tangan si anak yang mengepal sampai akhir hayatnya karena menahan sakit. Iya, dua hari terakhir itu dia selalu mengerang kesakitan, satu hal yang pasti membuat semua orang tidak tega untuk melihat dirasakan seorang anak kecil. Di sampingnya ada kedua orang tuanya yang kelihatan sangat hancur. Saya sampai tidak tega untuk menyapa dan menyampaikan apapun.
Esoknya si anak dibawa ke mesjid untuk disholati keluarga dan warga sekitar. Yang memimpin sholat ghoib itu bapak-bapak yang sepertinya salah satu pengurus mesjid. Setelahnya, saya lupa bapak-bapak itu ceramah apa. Yang jelas, setelah sebagian orang bubar, bapak itu menghampiri sepupu saya sambil bicara dalam bahasa Sunda “Turut berduka. Ya semoga segera diganti dengan (anak) yang baru”. Kalimat pertama masih oke, tapi kalimat kedua membuat saya tiba-tiba cukup kesal. “Anak yang baru? Terus kalau diganti, anak pertama tergantikan, gitu?” Oh iya, keponakan saya yang meninggal adalah putra pertama dan anak satu-satunya dari sepupu saya. Jadi seharusnya terbayang seberat apa kejadian ini bagi pihak orang tua. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa kesal, tapi saya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai detik itu, saya saja masih berpikir harus menyampaikan apa ke sepupu saya. Tidak harus mendoakan pengampunan dosa dan masuk surga, karena anak sekecil itu sudah terjamin surganya, beda dengan kita. Akhirnya saya cuma bisa peluk sambil bilang “Nanti insya Allah pasti ketemu lagi”.
Karena kejadian itu, saya jadi berpikir, sepertinya banyak orang tidak tahu adab menghadapi orang berduka, terlebih pada orang tua yang kehilangan anaknya. Saya pernah baca tulisan seorang kawan saat dia ditinggal meninggal ibunya. Dia agak terganggu dengan perkataan para pelayat seperti “Jangan sedih terus, ya. Yang kuat”. Apa rasionalisasi mereka untuk meng-invalidasi kesedihan keluarga yang ditinggalkan? Kenapa jangan sedih? Semua orang berhak untuk merasakan dan mengolah rasa mereka sendiri. Bahkan kalimat “Turut berduka cita” saja jika tidak disampaikan dengan tepat, bisa malah melukai perasaan, karena yang ditinggalkan bisa jadi merasa “Kalian tidak mengalami ini. Jadi kalian tidak akan mengerti rasanya. Jangan bilang turut berduka, karena yang kita rasakan itu tidak sama”. Sebegitu tricky-nya kalimat yang harus kita keluarkan di momen orang berduka.
Bicara tentang kehilangan anak, saya lantas jadi teringat bahwa ibu saya pun pernah mengalami hal serupa. Di tahun 1997 kakak saya no.3 meninggal karena sakit. Saya jadi cerita ke ibu tentang kalimat bapak-bapak mesjid itu yang saya rasa kurang berkenan, dan saya tanya ibu bagaimana rasanya ditinggal anak, saat ibu sebenarnya masih punya empat anak yang lain. Kata ibu, rasanya tetap tidak tergantikan (seperti yang saya duga). Saat itu ibu sampai stress dan harus bertemu psikolog (sesuatu yang saat itu belum lazim dilakukan, apalagi oleh keluarga kami) saking beratnya. Hancurnya sampai sekarang. Ibu tidak mau sedih, tapi ibu juga tidak mau kalau harus membicarakannya lagi. “Mending gak usah dibahas”, kata ibu. Raut wajahnya langsung berubah.
Kehilangan orang yang berarti pasti berat. Menghadapi orang yang mengalaminya, kita harus punya adab. Kalau tidak mengerti betul harus bicara apa, lebih baik diam saja. Jika memang punya itikad baik, saya pikir, yang penting kita hadir, menemani, agar yang kehilangan merasa setidaknya kita ada. Saya pun masih belajar. Semoga kita semua bisa belajar juga.
Dalam kenangan penuh kasih,

Muhammad Arvino (Mar 2019 – Jan 2024)